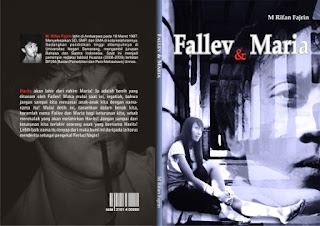Kesunyian Maria, Bagian 1
Lama sekali Maria mematung di
depan jendela berlapis perunggu kamarnya. Di luar hujan masih turun dengan
gerimis. Sesekali ia melongok ke luar jendela, dibiarkannya rintik-rintik hujan
menyapu wajahnya. Sementara irama denting air hujan yang menimpa genteng
rumahnya, menyatu dengan detak jantungnya yang berdebar-debar menantikan kedatangan Fallev.
Remang-remang senja semakin mendekap kesunyian Maria.
“Fallev, bukankah kau telah
berjanji tak akan membiarkanku lama menunggu?” dia berbisik, kemudian berbalik
dan berjalan menapaki lantai marmer kamarnya yang luas. Kakinya yang semakin
lemah membawanya menuju cermin besar di sudut kamarnya.
Maria duduk di kursi rias
berukir bunga-bunga yang terbuat dari gading. Di depan cermin berlapis perak
itu, Maria dapat melihat bayangan sekujur tubuhnya.
“Oh, apakah aku harus
membiarkan wajahku semakin keriput tanpa ada satu hal pun yang dapat kukerjakan
selain menunggu?” Maria meraba wajahnya. Kecemasan mulai merayap di dadanya,
dan semakin menjadi saat matanya menangkap bayangan rambutnya, “Rambutku pun
mulai bertambah putih hari demi hari. Oh, Fallev, terkutuk kau membiarkanku
tersiksa seperti ini!”
Maria berlari dan membanting
tubuhnya di kasur. Terisak-isak ia menangis. Di kamar yang luas itu, tak terdengar
apa pun selain isak tangis Maria dan bunyi air hujan yang turun semakin deras.
“Fallev, apakah kau masih
berarti bagiku? Bukankah tak ada saat aku membutuhkanmu sama artinya dengan tak
berarti?”
Kesepian dan kesunyian adalah
problem terbesar Maria. Pot-pot porselen, lampu-lampu kristal, ukir-ukiran dari
kayu cemara, batu-batu permata, serta butir-butir berlian yang terpasang dengan
cermat dan sangat rapi di lemari-lemari kamar itu, sedikit pun tak mampu
menghibur Maria. Taman-taman bunga dengan air mancur yang senantiasa mengalir
membasahi bunga-bunga itu, juga tak dapat menghibur hati Maria.
Kemewahan-kemewahan itulah
yang dirasakan oleh Maria sebagai penambah kesepian saja, yang justru semakin
memperburuk kekosongan batin Maria. Kesemuanya hanya nampak indah saat mata
ingin memandang, tetapi sedikit pun tak dapat berbuat apa-apa. Mereka tak mampu
tersenyum atau tertawa saat Maria bahagia. Mereka tak mampu bermuram durja atau
menangis saat Maria bersedih. Atau saat Maria sekadar membutuhkan teman berbincang,
mereka hanya terdiam dalam bisu.
Kadang Maria menyesalkan
mengapa ia menurut saja kemauan Fallev hidup sendirian, membangun kebahagiaan
hanya berdua saja. Dalam benak Maria, alangkah indahnya membangun satu rumah
tangga bersama Fallev, bertumpu pada satu cinta dan janji yang telah diucapkan
mereka berdua. Bukankah sangat indah ketika salah satu dari Fallev atau Maria
terserang demam, kemudian salah satu dari mereka dengan setia menemani dan
menjaga hingga kesembuhannya? Bukankah sangat manis ketika Maria tengah dilanda
kecemasan dan ketakutan yang amat sangat lantas Fallev mendekat dan memeluknya
hingga terlelap dan hilang semua kecemasan dan ketakutannya? Bukankah mereka
dapat menjelma menjadi satu keluarga yang sangat bahagia ketika mereka berdua
dapat memasak bersama, sarapan pagi, makan siang, dan merancang sebuah makan
malam yang romantis setiap harinya? Kemudian, keindahan-keindahan dan
kebahagiaan itu semakin lengkaplah dengan kelahiran seorang putra yang dapat
menyejukkan mata. Begitulah yang terbayang di benak Maria dahulu.
Sebenarnya dulu bisa saja
Maria membawa Liesha, gadis kecil yang penurut untuk membantu kesibukan rumah
tangganya. Menurutnya tak ada yang akan berkeberatan jika Maria menginginkan
hal itu. Ayah dan ibu Maria tak akan mungkin melarangnya, pembantu di rumah
sudah cukup untuk membereskan segala keperluannya. Sedangkan Marie, ibu Liesha,
yang telah mengabdikan hidupnya untuk membantu keluarga Maria, tentu juga
dengan senang hati melepasnya, dan justru permintaan itu akan menjadi satu
kebanggaan baginya.
Namun Fallev tak
menginginkannya. Entahlah, apa yang diangankan Fallev saat itu. Sekarang
keadaan telah cukup jelas. Maria kini menyadari bahwa keputusannya mengiyakan
permintaan Fallev saat itu adalah satu keputusan bodoh. Mungkin tidak bagi
Fallev, tapi bagi Maria sendiri, keputusan itu sekarang dirasakannya sangatlah
buruk.
Maria mencoba terpejam. Ia
menarik selimut tebal untuk menutup seluruh tubuhnya, dan menyembunyikan
wajahnya, seolah ingin sejenak menghapus segala beban pikirannya. “Aku tak ‘kan
biarkan otakku berpikir tentangmu terus-menerus, Fallev,” pikirnya.
Hujan belum juga mereda.
Kilat-kilat cahaya menyilet langit dengan sesekali disertai petir yang
memekakkan, membenamkan Maria ke dalam tidurnya yang lelap, meninggalkan segala
kebosanan yang telah mencapai titik tertinggi di dada Maria.
Sementara beberapa kilometer
dari ranjang Maria, pada tanah-tanah yang basah, terdengarlah tapak-tapak dua
ekor kuda putih yang berjalan cepat menarik kereta. Dua buah garis yang lurus
sejajar telah terlukis.
Di atas kereta, seorang lelaki
bertopi lebar melecut-lecutkan cambuk seiring teriakannya yang bersemangat.
Raut wajahnya dapat mengatakan, bahwa ia sungguh-sungguh tak sabar. Di belakang
tempat ia duduk memacu kereta, peti-peti yang dibawanya semuanya telah kosong.
Ia tersenyum penuh kemenangan.
Ia merasa menjadi orang yang sungguh paling beruntung. Senja yang berwarna
buram, sangat bertolak dengan suasana hatinya yang cerah dan berbunga. Derasnya
hujan pun baginya sangat sejalan dengan anugrah yang didapatkannya.
Lelaki itu semakin mempercepat
laju keretanya. Ia kembali tersenyum, semakin lebar. Kini ia dapat melihat atap
istananya. “Aku segera sampai, Maria. Aku sudah sangat rindu untuk segera
mendekapmu. Baik-baik sajakah kau, Maria?” teriaknya. Lelaki itu, tak lain
adalah Fallev, yang telah sangat dinanti Maria.
Ia menghentikan laju
keretanya, menarik napas dalam-dalam dan merentangkan kedua tangannya. Ia
menatap langit, “Akulah orang terhebat di dunia! Tak ada yang mampu menandingi
aku!”
Ia meloncat turun dari
keretanya, membiarkan dua kuda putihnya yang telah dengan sendirinya berjalan
menuju kandang mereka. Sedangkan perkara menurunkan peti-peti dan menyimpan
keretanya, bisa belakangan, pikir Fallev. Segera dengan langkah-langkah lebar
ia berlari menapaki pekarangan rumahnya. Ia sama sekali tak peduli sepatunya
akan basah dan kotor.
“Maria...!” teriak Fallev
memanggil istrinya.
Sekali lagi. Rumah itu terlalu
luas dan sunyi. Tak ada jawaban. Fallev melemparkan topi lebarnya ke sofa.
“Maria? Hm, mungkin ia sedang
tertidur.”
Fallev segera naik menyusuri
tangga yang berputar menuju kamarnya.
“Maria, kau tak menyambut
kedatanganku?”
Pintu kamar itu tertutup.
Perlahan Fallev membukanya pintu berukir bunga-bunga itu. Ia tersenyum, dan
berjingkat mendapati istrinya yang berselimut. Ia duduk di samping Maria,
menyibakkan pelan-pelan selimut yang menutup wajah Maria. “Maria, kau tak
berubah...”
Fallev meraba saku mantelnya,
mengambil sesuatu yang ingin ia berikan kepada istrinya, sebuah kalung emas.
“Maria, lihat apa yang aku
bawakan untukmu!”
Dengan hati-hati Fallev
memasang kalung itu di leher Maria. Diusapnya kening Maria, lalu menciumnya.
Sesaat kemudian mata Maria terbuka. Ia terbangun.
“Fallev?” Maria bangkit. Ia
tak dapat menahan kegembiraan menyadari Fallev telah berada di hadapannya.
Dipeluknya Fallev.
“Fallev, aku kira kau lupa
jalan pulang, aku sempat menyangka kau tak ‘kan kembali lagi,” ucap Maria di
sela isak tangisnya yang tersisa.
Bersambung ke bagian 2 klik di sini....